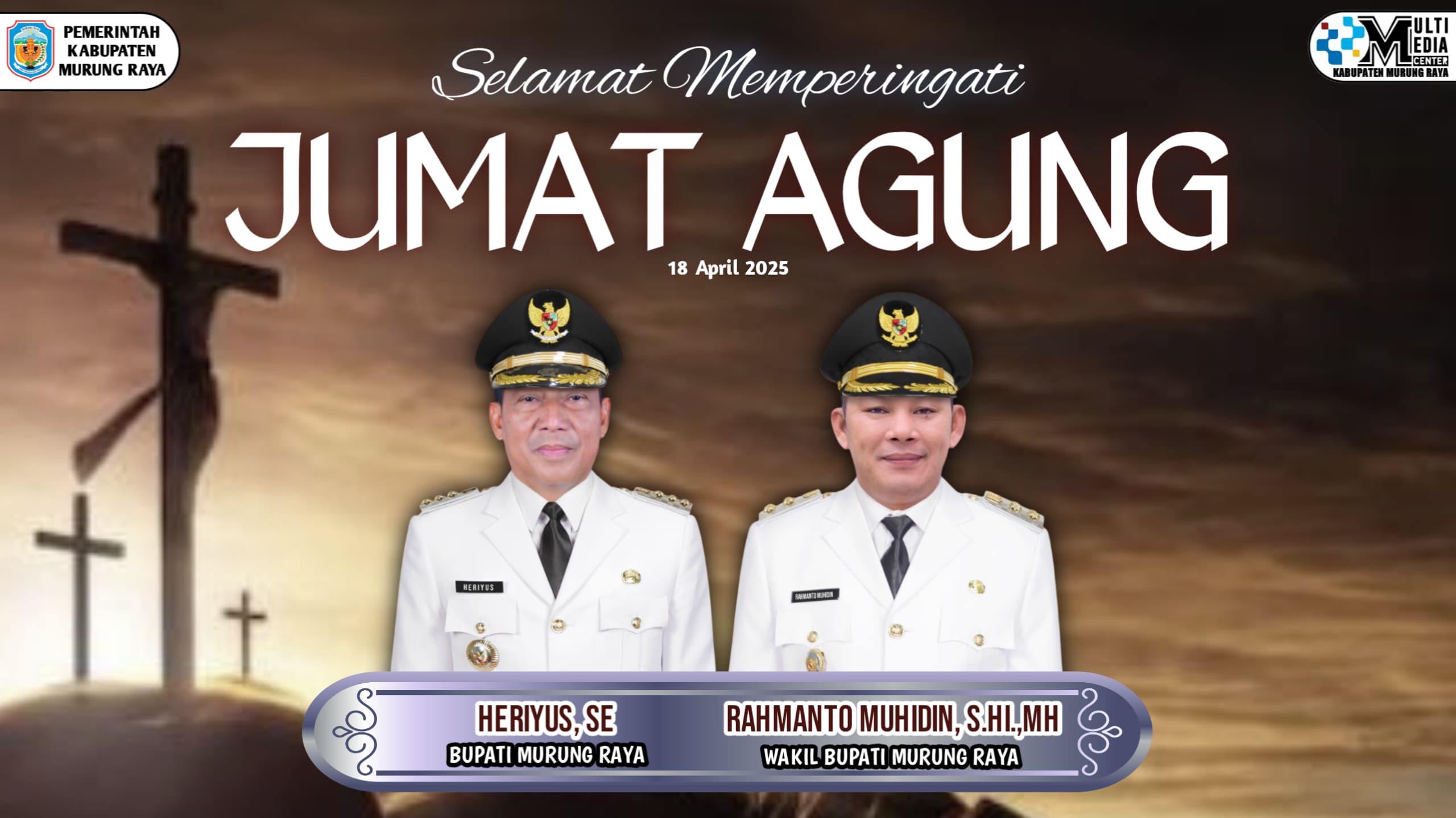Kepulauan Riau, Sibernasionalnews.com – Laut Kepulauan Riau kini tak lagi milik publik. Data geoportal Minerba One Map ESDM mengungkap fakta mencengangkan: lebih dari 115 izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan di perairan Kepri, mencakup luas area 132.000 hektare lebih. Komoditas yang diburu: pasir laut, pasir kuarsa, dan timah.
Wilayah tambang tersebar di Batam, Bintan, hingga Karimun, bahkan merangsek masuk ke zona 12 mil laut, wilayah tangkapan utama nelayan tradisional.
> “Ini adalah bentuk nyata ocean grabbing oleh korporasi, seperti yang terjadi di Tangerang. Laut yang seharusnya untuk nelayan, kini dikuasai pemilik modal,” ujar Parid Ridwanuddin, peneliti kelautan dari Auriga Nusantara.
Pemerintah Klaim Legal, Nelayan Merasa Dikhianati
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Kepala Dinas ESDM, Muhammad Darwin, menyatakan bahwa wilayah tambang sudah diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang telah dikonsultasikan secara publik.
Namun, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri membantah keras klaim tersebut.
> “Kami hanya diajak sosialisasi awal. Saat pembahasan hingga draf final, kami tidak dilibatkan. Kami menolak alokasi ruang tambang yang besar di laut,” tegas Distrawandi, Ketua HNSI Kepri.
Distrawandi menambahkan, sejak terbitnya PP No. 26 Tahun 2023 yang membuka kembali ekspor pasir laut, keresahan nelayan meningkat. Meski Mahkamah Agung telah membatalkan pasal ekspor pasir dalam aturan tersebut, ancaman eksploitasi laut tetap tinggi.
> “Kalau pemerintah mau rusak lingkungan Kepri, katakan saja terang-terangan. Jangan rakyat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Ketimpangan Data dan Potensi Kerusakan Ekosistem
Kementerian ESDM menyebut hanya ada lima pemegang IUP produksi di perairan Kepri. Namun, data di laman MODI (Minerba Online Data Indonesia) mencatat lebih dari 15 perusahaan telah mengantongi IUP produksi.
Alfarhat Kasman dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti bahwa pertambangan laut membawa daya rusak ekologis yang luar biasa, mulai dari kekeruhan air, kerusakan terumbu karang, hingga hilangnya habitat ikan yang menjadi andalan nelayan.
> “Tambang laut itu sama saja membunuh nelayan secara perlahan. Wilayah tangkap menyempit, hasil ikan turun, dan mereka dipaksa melaut lebih jauh.”
Dampak Geopolitik dan Kriminalisasi Nelayan
Kepri adalah provinsi kepulauan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Laut China Selatan. Kerusakan ekosistem laut di wilayah ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal kedaulatan negara.
> “Tahun lalu, 23 nelayan Kepri ditangkap karena melaut hingga ke perairan negara lain. Mereka terpaksa keluar karena laut kita sendiri sudah rusak,” kata Yonvitner, ahli kelautan IPB University.
Menurutnya, penguasaan ruang laut oleh korporasi tambang harus dilihat dari kacamata geopolitik, bukan sekadar ekonomi. “Jika ini dibiarkan, maka ancaman terbesar Kepri bukan dari luar negeri, tapi dari regulasi dan izin yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah.”
Langgar UU Pesisir dan Semangat Ekonomi Biru
Keberadaan WIUP dan IUP di laut Kepri dinilai bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 UU tersebut secara tegas melarang penambangan pasir laut, dan Pasal 73 mengatur sanksinya.
Parid Ridwanuddin menilai kebijakan tambang laut justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi biru.
> “Kalau ruang laut jadi tambang, darimana lagi kita dapat ikan dan hasil laut? Jangan sampai Kepri yang selama ini dikenal sebagai penghasil pangan laut terbesar di Sumatera justru kehilangan identitasnya.”
Desakan: Moratorium Tambang Laut dan Audit Perizinan
Berbagai elemen sipil, termasuk JATAM, Auriga, dan HNSI, mendesak moratorium total terhadap tambang laut di Kepri dan pembatalan WIUP yang telah diterbitkan.
Mereka juga menuntut audit menyeluruh terhadap proses penerbitan izin dan evaluasi keterlibatan publik dalam dokumen RZWP3K.
—
Catatan Redaksi:
Kepulauan Riau adalah jantung laut Indonesia. Dengan 96% wilayahnya berupa lautan, Kepri seharusnya dijaga sebagai wilayah pangan, konservasi, dan kedaulatan—bukan dijadikan ladang eksploitasi korporasi.
Jika ruang laut diubah jadi wilayah tambang, yang hilang bukan hanya ekosistem dan nelayan, tetapi masa depan kita sebagai bangsa maritim.
 Langsung ke konten
Langsung ke konten